BuolPedia - Catatan Belanda: Sejarah dan Transformasi Wilayah Buol Dari Pemerintahan Adat hingga Reorganisasi 1913
Belanda menjajah Indonesia, termasuk wilayah Buol yang sekarang masuk Provinsi Sulawesi Tengah, dan meninggalkan banyak catatan penting yang kini menjadi arsip sejarah berharga.
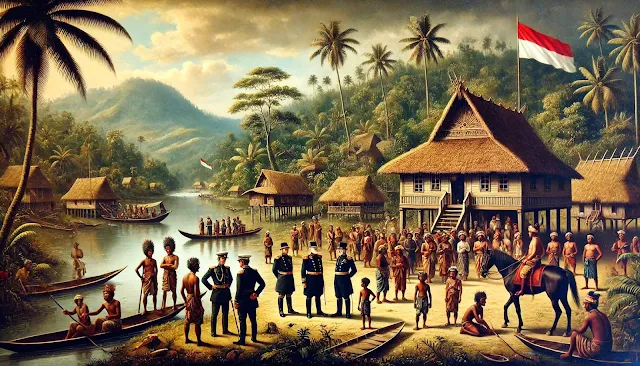 |
| Ilustrasi saat Belanda menjajah rakyat Buol. Gambar dihasilkan menggunakan teknologi AI |
Salah satu dokumen yang mencatat sejarah Buol adalah buku "Kumpulan Hukum Adat", yang disusun oleh Komisi untuk Hukum Adat dan diterbitkan oleh Institut Kerajaan untuk Ilmu Bahasa, Geografi, dan Etnologi Hindia Belanda pada tahun 1919.
Artikel ini membahas Sejarah dan Transformasi Wilayah Bwool, mulai dari pemerintahan adat hingga reorganisasi tahun 1913, berdasarkan isi buku tersebut, yang menjadi referensi penting dalam memahami perjalanan sejarah dan hukum adat di Sulawesi, khususnya di Buol.
Sejarah dan Struktur Sosial di Kabupaten Buol: Dari Masa Lalu Hingga Reorganisasi 1913
Kabupaten Buol, yang terletak di pantai utara Sulawesi, memiliki sejarah panjang yang dipenuhi dengan dinamika sosial dan pemerintahan.
Dari pemukiman awal yang tersebar di lembah hingga reorganisasi politik pada awal abad ke-20, wilayah ini mengalami banyak perubahan dalam struktur pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam.
Asal Usul dan Kehidupan Masyarakat Buol
Suku Buol hidup di wilayah yang dikenal sebagai dataran Buol, yang terletak di sekitar dua sungai besar: Sungai Buol di sebelah barat dan Sungai Kantanan di sebelah timur.
Masyarakat Buol pada masa lalu terbagi menjadi dua kelompok utama berdasarkan lokasi mereka, yakni wilayah di sekitar Sungai Kantanan dan wilayah di sekitar Sungai Buol.
Pembagian wilayah ini juga diikuti dengan pembagian kekuasaan, di mana setiap kelompok dipimpin oleh seorang panggoeloe (pemimpin).
Mereka membuka ladang dengan cara yang sangat hati-hati, seringkali dengan menebang pohon untuk membuat ruang untuk bercocok tanam. Sumber daya alam seperti hutan dan laut menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka.
Setiap panggoeloe memiliki hak untuk mengatur tanah dan sumber daya alam di wilayahnya, tetapi dengan satu kesepakatan penting: mereka semua harus mendapatkan pengakuan dari Sultan di Ternate, yang menjadi pemimpin politik tertinggi di wilayah ini.
Pada saat itu, tanah di wilayah Buol tidak dimiliki secara pribadi oleh individu, melainkan dimiliki oleh komunitas secara keseluruhan. Meskipun begitu, setiap anggota suku berhak untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan kebutuhannya, terutama dalam hal pertanian dan perikanan.
Bahkan orang asing yang datang ke wilayah tersebut pun dapat mengakses sumber daya alam, dengan syarat bahwa mereka bekerja sama dengan warga setempat dalam pembukaan ladang atau kegiatan ekonomi lainnya.
Sistem pertanian yang diterapkan oleh masyarakat Buol juga cukup unik. Mereka menanam berbagai macam tanaman seperti padi, millet, dan kacang-kacangan. Tanah pertanian di Buol seringkali dibagi-bagi dalam ladang-ladang yang tersebar, dengan jarak yang cukup jauh satu sama lain.
Pada tanah yang lebih datar atau lebih luas, ladang-ladang bisa berada berdekatan, dan biasanya ladang-ladang ini dibatasi dengan pagar untuk melindungi tanaman dari babi hutan dan rusa yang banyak ditemukan di daerah tersebut.
Dalam reorganisasi ini, setiap distrik tetap dipimpin oleh seorang marsaoleh (kepala distrik), sementara radja (pemimpin tertinggi) tetap memegang peran utama dalam pemerintahan lokal.
Penting untuk dicatat bahwa meskipun ada pembagian administratif ini, sistem pemerintahan tradisional yang berlandaskan pada adat tetap dipertahankan. Para pemimpin daerah tetap diberikan otoritas untuk mengatur wilayah masing-masing, namun dengan pengakuan resmi dari pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu.
Sistem pemerintahan ini bertujuan untuk memperkuat kontrol terhadap wilayah tersebut dan memastikan kelangsungan pemerintahan adat yang sudah ada sejak lama.
Selain itu, perubahan penting lainnya adalah pengakuan terhadap hak-hak tanah oleh pemerintah kolonial. Sejak zaman dahulu, tanah di wilayah Buol tidak dimiliki oleh individu, melainkan oleh komunitas adat.
Setiap anggota suku memiliki hak untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan kebutuhannya, namun hak-hak ini juga diatur oleh adat dan kesepakatan bersama.
Setiap anggota suku yang berhak (berdasarkan adat) dapat memanfaatkan tanah tersebut, baik untuk pertanian, pembukaan ladang, atau pemanfaatan hutan dan laut.
Namun, untuk memastikan bahwa hak atas tanah ini tidak disalahgunakan, terdapat aturan adat yang mengatur siapa yang dapat menggunakan tanah dan bagaimana proses pembukaan ladang dilakukan.
Biasanya, untuk membuka lahan pertanian, seseorang harus terlebih dahulu menandai batas-batas tanah yang ingin digarap, dan ini diakui sebagai hak preferensi untuk tanah tersebut.
Hasil-hasil ini tidak hanya dimanfaatkan untuk konsumsi pribadi, tetapi juga diperdagangkan, sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi masyarakat Buol.
Setiap warga yang menghasilkan produk dari alam diwajibkan membayar pajak kepada pemerintah, baik dalam bentuk barang maupun uang.
Pajak yang dikenakan pada masyarakat Buol bervariasi, tergantung pada jenis produk yang dihasilkan. Sebagai contoh, pajak untuk produk pertanian seperti padi, milou, dan kacang-kacangan adalah sepuluh persen dari hasil yang diperoleh.
Demikian juga dengan produk hutan dan laut, yang dikenakan pajak dengan persentase tertentu. Pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah tersebut.
Pajak ini mencakup berbagai jenis usaha, termasuk pertanian, perikanan, dan pertambangan emas, yang merupakan salah satu sumber daya alam utama di daerah tersebut.
Meskipun ada perubahan yang terjadi akibat pengaruh pemerintahan kolonial Belanda, prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam adat tetap menjadi landasan kehidupan mereka.
Dengan reorganisasi yang terjadi pada tahun 1913, wilayah Buol mengalami pembagian administratif yang jelas, dengan setiap distrik dipimpin oleh seorang marsaoleh yang tetap menjaga tradisi pemerintahan adat.
Selain itu, sistem pengelolaan tanah dan sumber daya alam tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Buol, yang mengandalkan hasil alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Seiring berjalannya waktu, meskipun terjadi perubahan-perubahan dalam struktur pemerintahan dan kebijakan pajak, nilai-nilai adat dan cara hidup tradisional masyarakat Buol tetap bertahan sebagai bagian penting dari identitas mereka.
Pembagian wilayah dan kepemimpinan ini menciptakan empat kawasan utama, yakni Biaoe (di sebelah barat), Talaki (di sebelah timur), Tongon (di bagian barat wilayah), dan Bonobogoe (di bagian timur).
Menurut cerita rakyat, masyarakat Buol pada awalnya hidup berdampingan dengan alam dan mengandalkan hasil alam seperti hasil pertanian dan perikanan.
Mereka membuka ladang dengan cara yang sangat hati-hati, seringkali dengan menebang pohon untuk membuat ruang untuk bercocok tanam. Sumber daya alam seperti hutan dan laut menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka.
Pembagian Wilayah dan Pengaruh Raja
Pada masa lalu, wilayah Buol dikuasai oleh empat panggoeloe yang memimpin masing-masing daerah tersebut.
Setiap panggoeloe memiliki hak untuk mengatur tanah dan sumber daya alam di wilayahnya, tetapi dengan satu kesepakatan penting: mereka semua harus mendapatkan pengakuan dari Sultan di Ternate, yang menjadi pemimpin politik tertinggi di wilayah ini.
Pada saat itu, tanah di wilayah Buol tidak dimiliki secara pribadi oleh individu, melainkan dimiliki oleh komunitas secara keseluruhan. Meskipun begitu, setiap anggota suku berhak untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan kebutuhannya, terutama dalam hal pertanian dan perikanan.
Bahkan orang asing yang datang ke wilayah tersebut pun dapat mengakses sumber daya alam, dengan syarat bahwa mereka bekerja sama dengan warga setempat dalam pembukaan ladang atau kegiatan ekonomi lainnya.
Sistem pertanian yang diterapkan oleh masyarakat Buol juga cukup unik. Mereka menanam berbagai macam tanaman seperti padi, millet, dan kacang-kacangan. Tanah pertanian di Buol seringkali dibagi-bagi dalam ladang-ladang yang tersebar, dengan jarak yang cukup jauh satu sama lain.
Pada tanah yang lebih datar atau lebih luas, ladang-ladang bisa berada berdekatan, dan biasanya ladang-ladang ini dibatasi dengan pagar untuk melindungi tanaman dari babi hutan dan rusa yang banyak ditemukan di daerah tersebut.
Reorganisasi 1913: Pembagian Wilayah dan Perubahan Pemerintahan
Pada tahun 1913, terjadi perubahan besar dalam struktur pemerintahan wilayah Buol. Wilayah tersebut dibagi menjadi tiga distrik: Biaoe, Bonobogoe, dan Paleleh.
Pembagian ini menciptakan batas yang jelas antara distrik-distrik tersebut, dan Sungai Buol menjadi garis pembatas utama.
Dalam reorganisasi ini, setiap distrik tetap dipimpin oleh seorang marsaoleh (kepala distrik), sementara radja (pemimpin tertinggi) tetap memegang peran utama dalam pemerintahan lokal.
Penting untuk dicatat bahwa meskipun ada pembagian administratif ini, sistem pemerintahan tradisional yang berlandaskan pada adat tetap dipertahankan. Para pemimpin daerah tetap diberikan otoritas untuk mengatur wilayah masing-masing, namun dengan pengakuan resmi dari pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu.
Sistem pemerintahan ini bertujuan untuk memperkuat kontrol terhadap wilayah tersebut dan memastikan kelangsungan pemerintahan adat yang sudah ada sejak lama.
Selain itu, perubahan penting lainnya adalah pengakuan terhadap hak-hak tanah oleh pemerintah kolonial. Sejak zaman dahulu, tanah di wilayah Buol tidak dimiliki oleh individu, melainkan oleh komunitas adat.
Setiap anggota suku memiliki hak untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan kebutuhannya, namun hak-hak ini juga diatur oleh adat dan kesepakatan bersama.
Di masa reorganisasi 1913, pengelolaan tanah dilakukan secara lebih terstruktur, dengan adanya pembagian hak dan kewajiban yang jelas antara anggota suku.
Hak atas Tanah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Buol adalah hak mereka terhadap tanah dan sumber daya alam. Tanah yang digunakan untuk bertani atau berburu tidak dianggap sebagai milik pribadi, tetapi dimiliki secara kolektif oleh masyarakat.
Setiap anggota suku yang berhak (berdasarkan adat) dapat memanfaatkan tanah tersebut, baik untuk pertanian, pembukaan ladang, atau pemanfaatan hutan dan laut.
Namun, untuk memastikan bahwa hak atas tanah ini tidak disalahgunakan, terdapat aturan adat yang mengatur siapa yang dapat menggunakan tanah dan bagaimana proses pembukaan ladang dilakukan.
Biasanya, untuk membuka lahan pertanian, seseorang harus terlebih dahulu menandai batas-batas tanah yang ingin digarap, dan ini diakui sebagai hak preferensi untuk tanah tersebut.
Jika tanah sudah ditinggalkan atau tidak dikelola lagi, hak ini bisa jatuh ke orang lain yang kemudian menandai tanah tersebut sebagai miliknya.
Selain pertanian, sumber daya alam seperti hutan dan laut juga sangat penting bagi kehidupan masyarakat Buol. Mereka mengandalkan hasil hutan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti damar, rotan, kayu, dan lainnya. Begitu juga dengan hasil laut yang meliputi ikan, tripang, dan penyu.
Hasil-hasil ini tidak hanya dimanfaatkan untuk konsumsi pribadi, tetapi juga diperdagangkan, sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi masyarakat Buol.
Sistem Pajak dan Keuangan dalam Pemerintahan Buol
Seiring dengan reorganisasi yang terjadi pada tahun 1913, sistem pajak juga mengalami perubahan yang signifikan. Dalam sistem tradisional, pajak dikenakan atas hasil pertanian, produk hutan, dan hasil laut.
Setiap warga yang menghasilkan produk dari alam diwajibkan membayar pajak kepada pemerintah, baik dalam bentuk barang maupun uang.
Pajak yang dikenakan pada masyarakat Buol bervariasi, tergantung pada jenis produk yang dihasilkan. Sebagai contoh, pajak untuk produk pertanian seperti padi, milou, dan kacang-kacangan adalah sepuluh persen dari hasil yang diperoleh.
Demikian juga dengan produk hutan dan laut, yang dikenakan pajak dengan persentase tertentu. Pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah tersebut.
Namun, pada tahun 1914, pajak ini diganti dengan pajak atas pendapatan dari bisnis dan usaha lainnya, sebagai bagian dari upaya untuk merasionalisasi sistem pajak dan meningkatkan pendapatan pemerintah.
Pajak ini mencakup berbagai jenis usaha, termasuk pertanian, perikanan, dan pertambangan emas, yang merupakan salah satu sumber daya alam utama di daerah tersebut.
Kesimpulan
Wilayah Buol memiliki sejarah yang kaya dan beragam dalam hal kehidupan sosial, budaya, dan pemerintahan.
Dari sistem pemerintahan adat yang terstruktur dengan baik hingga perubahan besar yang terjadi pada awal abad ke-20, masyarakat Buol tetap mempertahankan kearifan lokal mereka dalam mengelola sumber daya alam dan tanah.
Meskipun ada perubahan yang terjadi akibat pengaruh pemerintahan kolonial Belanda, prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam adat tetap menjadi landasan kehidupan mereka.
Dengan reorganisasi yang terjadi pada tahun 1913, wilayah Buol mengalami pembagian administratif yang jelas, dengan setiap distrik dipimpin oleh seorang marsaoleh yang tetap menjaga tradisi pemerintahan adat.
Selain itu, sistem pengelolaan tanah dan sumber daya alam tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Buol, yang mengandalkan hasil alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Seiring berjalannya waktu, meskipun terjadi perubahan-perubahan dalam struktur pemerintahan dan kebijakan pajak, nilai-nilai adat dan cara hidup tradisional masyarakat Buol tetap bertahan sebagai bagian penting dari identitas mereka.
Disarikan dari:
Datrechtbundels Bezorgd Door De Commissie Voor Het Adat Recht En Uitgegeven Door Het Koninklijk Instituut Voor De Taal-, Land- En Volken Kunde Van Nederlandsch-Indië Xvii: Celebes 'S-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1919

.png)

interesting story.....👍👍
BalasHapusTerima kasih Bang
Hapuskok aku malah fokus ke gambar AI nya ya... cakep banget, pake aplikasi apa sob?
BalasHapus